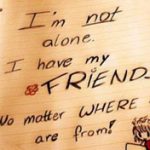“Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan: “Aku tidak membutuhkan engkau”… Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.”
(1 Korintus 12 : 21 – 22)
“Sejarah adalah sejarah yang tertulis. Sejarah lisan adalah dongeng karena tak ada kaitan bukti otentik. Maka jangan heran, jika Afrika adalah sebuah wilayah tanpa sejarah. Sejarah Afrika adalah sejarah orang Eropa di Afrika.” Pernyataan yang dikemukakan oleh Suka Hardjana, seorang dosen dan praktisi musik ini, sebenarnya sebuah pernyataan yang ingin menguji asal-usul dan kesahihan pemahaman sejarah itu menjadi milik penguasa. Mereka yang berkuasalah yang bisa membangun cerita, memberi nama, membuat ukurannya. Fakta selanjutnya, penguasa sering memosisikan dirinya sebagai hakim yang akan mengadili siapa saja yang melanggar ketentuan yang dibuatnya. Maka tak heran, Diponegoro adalah pemberontak, ketika sejarah ada di tangan pemerintah kolonial Belanda. Namun, setelah kita merdeka dan berdaulat sebagai bangsa, dan mulai belajar membangun sejarah kita sendiri, maka kini kita memberi nama pemberontak itu sebagai pahlawan.
Hal serupa di atas, ternyata juga berlaku dalam musik. Setiap kali kita bicara tentang sejarah musik, semua orang akan merujuk pada sejarah musik tertentu, yang tak lain adalah sejarah musik Eropa. Mengapa? Mereka menjadi yang lebih dulu menuliskannya; mereka menjadi yang pertama membakukannya. Mereka memosisikan diri sebagai kiblat yang akan diikuti, hingga hari ini. Tak heran, jika dulu kita dijajah dengan kekuatan meriam dan senapan, kini kita dijajah dengan copyright. Salah satu dosa besar pembuat sejarah adalah ketika mengukur pihak lain berdasarkan kebenarannya sendiri. Saya tidak bisa mengatakan seorang tamu yang meminum air di gelas dengan sekali tenggak, sebagai hal yang tidak sopan hanya karena kita menganggap bahwa sopan adalah ketika meminumnya sedikit demi sedikit. Tamu kita itu juga memiliki kaidah yang berbeda. Justru bagi dirinya, sopan itu ditunjukkan dengan caranya seperti itu.
Kesalahan besar yang sama juga ketika kita menilai musik tradisional (musik etnik) berdasarkan kaidah musik barat. Musik tradisional juga mempunyai ukuran dan kaidah-kaidahnya sendiri. Meski tanpa tulisan dan seolah tanpa ukuran, seperti musik Barat. Dalam sebuah acara I’Exposition Universelle, ajang pameran negara-negara kolonial, yang digelar di Paris 1889, banyak orang Eropa yang tidak bisa mengerti, mengapa para pemain gamelan dapat memainkan musik mereka tanpa partitur. Musik yang dimainkan sedemikian panjang, dan masing-masing tahu kapan harus mengakhirinya. Mereka tentu juga akan terheran bahwa frekuensi 440 hz, bukanlah ukuran penting dalam menetapkan titik nada. Hal yang mengherankan lagi, ketidakharmonian itu justru bisa menjadi harmoni, di mana semua telinga bisa menerima, bahkan menikmatinya. Rasanya, justru inilah kekuatannya.
Sebuah musik yang juga mampu memberikan sebuah pesan moral yang kuat, bahwa keindahan hidup bersama, kadang tidak harus didekati dengan kemutlakan kaidah dan aturan yang baku, beku dan kaku. Kelenturan, kemampuan memaklumi perbedaan, berpikir alternatif, juga tetap perlu diberikan ruang dalam kita membangun sebuah harmoni.
(Pdt. Natan Kristiyanto)